CIRCUS OF BOOKS (2019)
Rasyidharry
Juni 26, 2020
Bagus
,
Barry Mason
,
Documentary
,
Jeff Stryker
,
Karen Mason
,
Larry Flint
,
Rachel Mason
,
REVIEW
Tidak ada komentar
Terkait tema LGBT miliknya, Circus of Books mampu menyatukan elemen-elemen seperti persekusi
aparat, ketidakberpihakan hukum, agama, AIDS, keluarga khususnya parenthood, hingga dampak internet
terhadap industri pornografi. Semuanya saling terkait, menyatu mulus tanpa menghilangkan
fokus. Tapi yang membuat dokumenter ini spesial adalah protagonisnya, pasangan
suami-istri, Barry Mason dan Karen Mason. Khususnya Karen, yang sepanjang 92
menit durasi filmnya, mengalami setumpuk pertentangan batin sampai akhirnya
bertransformasi.
Rachel Mason selaku sutradara, merupakan puteri mereka.
Filmnya pun dibuka oleh rekaman home
video yang Rachel buat saat kecil. Kemudian, selama mewawancarai narasumber
termasuk Micah (sang kakak) dan Josh (sang adik), ketimbang menjadi sosok tak
terlihat di belakang kamera, wajah Rachel juga disorot, memperlihatkan
reaksi-reaksinya. Tujuannya tak lain melahirkan keintiman dan kesan personal.
Sekilas, Keluarga Mason tampak biasa. Barry dikenal lewat
senyum yang tak pernah luntur, sementara Karen merupakan sosok yang tegas,
figur pemimpin, sekaligus Yahudi yang taat. Baru ketika remaja, tiga bersaudara
itu tahu, bahwa orang tua mereka adalah pemilik Circus of Books, toko buku dan
pornografi gay (majalah, DVD, alat seks) yang legendaris. Terletak di West
Hollywood, California, toko ini ibarat suaka layaknya bar, di mana para gay
bisa berinteraksi secara bebas. Bahkan, gang belakang toko kerap jadi lokasi
orang-orang kehilangan keperjakaan. Gang itu disebut “Vaseline Alley”.
Semua berawal dari kesulitan finansial pada era 70an, yang
membuat Karen dan Barry nekat menawarkan diri menjadi distributor majalah
dewasa ternama Hustler buatan Larry Flint. Bisnis itu berkembang. Toko pun
didirikan, bahkan di satu titik, pasutri Mason turut memproduseri film-film
porno gay yang dibintangi Jeff Stryker. Tapi apa signifikansi sebuah toko
barang-barang hiburan dewasa?
Bagi kaum hetero, pornografi sebatas alat melampiaskan nafsu.
Tapi untuk gay, setidaknya mereka yang muncul sebagai narasumber, pada awal
kemunculannya, ada kebanggaan menonton para gay bercumbu dengan bebas tanpa
takut dihakimi. Berkat Circus of Books, beberapa orang tahu ia tidak sendiri di
dunia ini. Pun mengetahui apa yang dilakukan Karen dan Barry membuat sahabat
Rachel semasa SMA menyadari satu hal, bahwa saat tumbuh dewasa, individu tidak
harus menjalani hidup sesuai jalur yang dianggap “wajar” oleh masyarakat.
Karen dan Barry menginspirasi tanpa disadari dan diniati.
Keduanya tidak membenci LGBT, tidak berniat mengeksploitasi, tapi juga tak
terlibat dalam pergerakan kemanusiaan apa pun. Semua murni bisnis yang dirahasiakan
dari anak-anak mereka, yang wajib menundukkan kepala bila terpaksa harus diajak
memasuki toko. Rachel sendiri baru tahu kalau Circus of Books merupakan toko
porno semasa SMA. Fakta yang ia ketahui dari teman-teman, bukan orang tuanya.
Lalu tibalah kita pada penelusuran paling engaging, yakni seputar Karen. Dia
berasal dari keluarga religius, adalah seorang religius, dan mendidik
anak-anaknya agar menjadi religius. Karen bukan anti-LGBT, tapi menganggap itu
sebagai konsep yang berada di luar lingkup kehidupan pribadi. Alhasi, meski
dianggap sosok berpengaruh di komunitas gay, awalnya tak ada kebanggaan sedikit
pun dalam dirinya terkait apa yang ia dan sang suami lakukan. Hal itu nampak
saat beberapa kali Karen mengeluh pada
Rachel. “Kenapa kamu merasa ini pantas dijadikan dokumenter? Bagian mana yang
menarik? Seharusnya kamu membahas hal lain saja”.
Sampai suatu hari, ia terpukul kala menyadari bahwa LGBT
tidaklah “sejauh” itu, yang memancing dilema, mengingat agamanya mengharamkan
hubungan sesama jenis. “Apabila terkait orang lain, mungkin kamu tidak
bermasalah, tapi bagaimana jika itu menyangkut orang terdekatmu?”, jadi
pertanyaan dilematis yang berusaha Karen (dan mungkin juga penonton) jawab. Paruh
akhir Circus of Books fokus menyoroti
proses Karen. Bagaiamana ia mempelajari kitab suci demi memahami konteks
mengapa gay disebut sebagai “abomination”.
Proses ini termasuk salah satu pemberi dampak emosional terbesar filmnya. Kamu
bisa menjadi religius tanpa harus berpikiran sempit, dan sebaliknya, menjadi
liberal bukan berarti mewajibkanmu membenci religiuisitas.
Mengangkat tema kompleks, bahkan sempat beberapa kali
menyentuh ranah lebih kelam khususnya saat AIDS mewabah dan merenggut nyawa
orang-orang di sekitar karakternya dalam waktu berdekatan, tak membuat Circus of Books terkesan berat apalagi
depresif. Ingat, film ini melibatkan Ryan Murphy selaku produser eksekutif.
Kelakar-kelakar menggelitik, juga estetika cheesy
pornografi vintage, jadi alasan
filmnya tetap tampil menghibur. Circus of
Books adalah tontonan positif sekaligus penuh harap. Penutupnya
memperlihatkan akhir sebuah era, namun bukan akhir perjuangan. Perjuangan untuk
mencintai dan dicintai.
Available on NETFLIX
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)

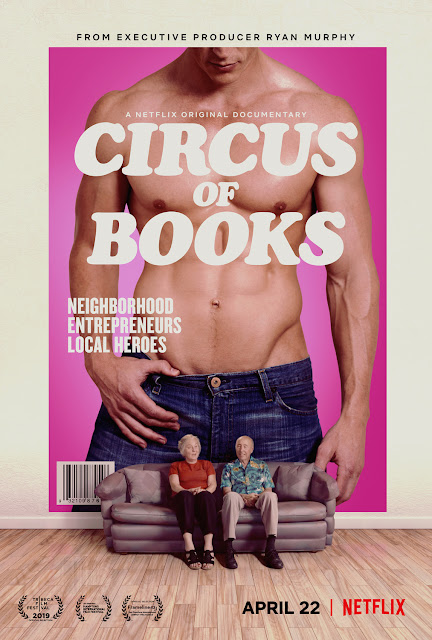









Tidak ada komentar :
Comment Page:Posting Komentar