REVIEW - DENDAM MALAM KELAM
"Edan film iki!", ujar penonton di sebelah saya selepas Dendam Malam Kelam mengungkap salah satu kejutannya. Banyak orang lain akan mengeluarkan respon serupa, yang mana sangat bisa dipahami, tapi remake dari film Spanyol berjudul The Body (2012) ini bukan semata mengandalkan twist, melainkan benar-benar disusun sebagai misteri yang solid dalam bercerita.
Semua berawal saat jenazah Sofia (Marissa Anita) lenyap dari kamar mayat laboratorium forensik. Arya (Bront Palarae), detektif yang bertugas mengusut misteri tersebut dan gemar bersumpah serapah memakai istilah "haram jadah" (entah kapan terakhir kali saya mendengar itu), memanggil suami Sofia, Jefri (Arya Saloka), untuk dimintai keterangan. Tapi ada satu hal yang polisi belum ketahui: Sofia bukan meninggal akibat serangan jantung, melainkan dibunuh oleh Jefri, yang ingin menutupi perselingkuhannya dengan Sarah (Davina Karamoy).
Baik di hadapan Arya ketika ia mengenakan topeng kebohongan, maupun saat tengah seorang diri dan secara bebas menunjukkan wajah aslinya pada penonton, Jefri selalu membantah telah mencuri jenazah mendiang istrinya. Bahkan di beberapa situasi, Arya nampak ketakutan dan begitu putus asa ingin menemukan pelaku sesungguhnya. Benarkah demikian, atau kita tengah menyaksikan sesosok unreliable narrator?
Dendam Malam Kelam memang piawai menyulut tanda tanya, yang berdampak pada terjaganya atensi penonton. Sewaktu tokoh-tokohnya berdebat, seperti saat Dr. Nadia (Putri Ayudya) melempar hipotesis bahwa Sofia mengalami mati suri yang segera dibantah oleh Arya, intensitasnya benar-benar mencuat berkat pengarahan Danial Rifki yang jeli mengolah ketegangan, pula akting para pemainnya.
Bagaimana Jefri bersikap songong sedari awal interogasi sehingga memancing kecurigaan polisi di saat semestinya ia berlaku sebaliknya memang cukup mengganggu, tapi seiring berjalannya waktu, Arya Saloka mampu membangun dinamika kuat bersama Bront Palarae melalui adu argumen keduanya. Di sisi lain, Marissa Anita dengan segala kepercayaan diri yang karakter Sofia miliki, tampil bak magnet berdaya tarik tinggi yang kemunculannya selalu meninggalkan kesan biarpun porsinya cenderung minim.
Tapi hal paling mengesankan dari Dendam Malam Kelam adalah bagaimana naskah adaptasi buatan Danial Rifki tetap mengutamakan kesolidan bertutur alih-alih mengandalkan twist semata. Tirai misterinya tak dibuka hingga akhir durasi, namun alurnya tetap padat sebab naskahnya tahu kapan harus membuka petunjuk baru, kapan harus mengajukan pertanyaan, kapan harus tancap gas, serta kapan harus berhenti sejenak. Penceritaannya rapi, dan twist hanyalah pemanis yang makin melengkapi presentasi.
Satu hal yang agak mengurangi tingkat kerapian kisahnya adalah beberapa pilihan departemen penyuntingan yang layak dipertanyakan, entah berupa transisi kasar, atau bentuk susunan antar adegan yang ada kalanya terasa kacau.
Pilihan sang sutradara terkait musik yang terkesan inkonsisten pun perlu dipertanyakan. Di satu titik, Dendam Malam Kelam terdengar elegan tatkala komposisi buatan Mondo Gascaro yang mengedepankan nuansa noir sedang mendominasi. Tapi di kesempatan lain, terutama saat flashback dramatis tengah terjadi, justru lagu pop mendayu-dayu yang mengiringi.
Mungkin itu cara Danial Rifki berkompromi dengan selera penonton awam Indonesia yang menyukai kesenduan dramatis. Setidaknya pilihan tersebut sempat efektif sewaktu kita diajak menyaksikan momen perkenalan Jefri dan Sofia. Menyakitkan rasanya melihat sesuatu yang diawali dengan keindahan harus diakhiri dengan kepiluan mematikan.
REVIEW - THE UGLY STEPSISTER
Berbeda dengan kisah semua umur yang dipopulerkan Disney, versi buatan Brothers Grimm (berjudul Aschenputtel) menyertakan bagian saat kakak tiri Cinderella memotong jari kakinya sendiri untuk menipu pangeran. Dipublikasikan pada tahun 1812, mungkin itu salah satu contoh cerita body horror paling awal sepanjang sejarah, terutama yang menerapkan elemen subgenre tersebut untuk menyinggung perihal "beauty is pain".
Emilie Blichfeldt selaku sutradara sekaligus penulis naskah menyadari subteks tersebut, kemudian melahirkan film yang terasa seperti anak haram dari perkawinan sinting antara Cinderella dan The Substance. Di sini Cinderella bernama Agnes (Thea Sofie Loch Næss). Masih seorang gadis berambut pirang yang cantik. Begitu cantik, sampai si kakak tiri, Elvira (Lea Myren), cuma bisa diam terpukau pada pertemuan perdana mereka.
Sebagaimana judulnya, The Ugly Stepsister bukan mengetengahkan sudut pandang Agnes, melainkan Elvira, yang harus bergulat dengan standar kecantikan masyarakat. Dia memakai kawat gigi, hidungnya tidak mancung, tubuhnya berisi, dagunya berlipat. Harapannya menikahi Pangeran Julian (Isac Calmroth) pun terasa bak mimpi di siang bolong.
Blichfeldt menekankan realisme dalam penokohannya. Cinderella dan sang ibu tiri, Rebekka (Ane Dahl Torp), bukan dua kutub berlawanan. Cinderella mengakui bahwa keputusan sang ayah, Otto (Ralph Carlsson) yang meninggal di malam pernikahan untuk mempersunting Rebekka didasari alasan finansial. Rebekka sendiri tidak mengetahui bahwa Otto telah bangkrut. Sederhananya, si ibu tiri yang selama ini cuma kita kenal kekejamannya, merupakan korban penipuan Cinderella dan sang ayah.
Karakter Elvira pun diberi kompleksitas serupa. Dia bukan lagi sebatas saudari tiri yang bersikap jahat karena bawaan lahir, melainkan produk dari betapa destruktifnya standar kecantikan. Selama 105 menit durasinya, The Ugly Stepsister menyuguhkan potret berisi tahap demi tahap kehancuran Elvira yang di awal hanyalah gadis naif yang mendambakan cinta, baik secara fisik atau psikis.
Seolah ingin menegaskan pesan "jangan menilai buku dari sampulnya", Blichfeldt menerapkan banyak kontradiksi di berbagai aspek filmisnya. Pemandangan yang sejatinya disturbing acap kali dikemas dalam bentuk komedi, misal saat Elvira menyambangi Dr. Esthétique (Adam Lundgren) guna memermak penampilan fisiknya. Kunjungan ke tempat praktik si dokter mengajak penonton menertawakan obsesi akan kecantikan, yang bisa mendorong individu melakukan tindakan yang bukan cuma ekstrim, juga konyol.
Penampilan Lea Myren membawa dampak serupa. Kecanggungannya dalam bertutur kata, bergestur, atau saat sebatas tersenyum, mampu memantik simpati sekaligus rasa geli secara bersamaan. Alhasil, ketimbang tragedi biasa, proses Elvira menjemput kehancuran pun tersaji sebagai tragikomedi.
Lihat pula bagaimana The Ugly Stepsister nampak luar biasa cantik, dengan tata artistik khas period drama yang dibanjiri kemewahan, sinematografi yang acap kali mengingatkan ke sinema era 60-an hingga 70-an, pula musik serba elegan. Padahal di balik segala keindahan tersebut, film ini menyimpan berbagai situasi khas body horror, yang bahkan bakal membuat pecinta horor veteran sekalipun ingin memalingkan wajah sejenak dari layar.
Pengarahan Blichfeldt tidak asal mengumbar kekerasan. Dia pastikan kamera terus merekam kala kekerasan itu terjadi, supaya penonton dapat mengobservasi sampai ke detail terkecil. Selain dibuat "menyaksikan", karena detail yang tersaji lengkap tersebut, kita pun digiring untuk "membayangkan", sehingga akhirnya turut "merasakan" pengalaman si karakter. Merinding, ngilu, mual, semuanya menyatu membentuk pengalaman sinematik sinting yang akan susah dilupakan.
REVIEW - WAKTU MAGHRIB 2
Sejak melakoni debut di Waktu Maghrib dua tahun lalu, Sidharta Tata telah membuat tiga film panjang (Ali Topan, Malam Pencabut Nyawa, Sakaratul Maut) dan dua serial (Pertaruhan: The Series, Zona Merah). Seolah telah menimba cukup ilmu, ia kembali untuk mengarahkan sekuelnya sebagai sosok yang berbeda. Bukan lagi pendatang baru, namun sutradara dengan kepercayaan diri tinggi yang telah menemukan kekhasannya.
Penonton yang pernah menyaksikan karya-karya lain Sidharta, baik film maupun serial, pasti tahu harus mengharapkan apa. Lupakan penampakan setor muka para hantu sebagaimana film pertama. Sang sineas lebih suka menghadirkan tawuran, aksi saling bacok, dan tentunya kejar-kejaran dengan aspek teknis memukau. Waktu Maghrib 2 seperti kompilasi dari setumpuk signature sang sineas.
Bahkan alih-alih setan, kita lebih dahulu melihat tawuran, yang terjadi selepas pertandingan sepakbola junior. Yugo (Sultan Hamonangan) turut terlibat, sementara sepupunya, Wulan (Anantya Kirana), yang terpaksa datang untuk mengantarkan botol minum, cuma bisa melihat dengan kesal. Bagi Wulan yang tengah fokus mengejar beasiswa, datang ke lapangan sungguh membuang waktunya.
Selanjutnya serupa film pertama. Tim sepakbola Yugo belum tiba di rumah pasca waktu maghrib menjelang, mengucapkan permintaan buruk tanpa pikir panjang, lalu selepas sebuah kecelakaan, beberapa dari mereka hilang. Yugo selamat, namun mendapati keanehan dalam diri Wulan yang ia yakini sudah kerasukan kala tersesat di hutan.
Fenomena yang Wulan alami memberi Anantya Kirana kesempatan membuktikan statusnya sebagai aktor muda Indonesia paling berbakat saat ini. Kenaturalan bocah 14 tahun ini di depan kamera sungguh luar biasa, bahkan melebihi banyak pelakon dewasa.
Hal paling mengganjal dari naskah buatan Sidharta Tata, Khalid Kashogi, dan Bayu Kurnia Prasetya adalah kurangnya penggalian terhadap mitologi mistis, yang melahirkan inkonsistensi "aturan". Kita melihat warga desa buru-buru mengajak anak mereka masuk ke rumah begitu maghrib tiba. Tapi rupanya si hantu dapat dengan mudah menyusup ke dalam rumah. Waktu Maghrib 2 membantah mitologinya sendiri tanpa memberi penjabaran memadai.
Kisahnya mengambil latar 20 tahun setelah peristiwa film pertama, dan Adi (Omar Daniel), salah satu bocah yang selamat dari tragedi sebelumnya, kini kembali untuk mengakhiri teror jin Ummu Sibyan. Jangan bayangkan perjalanan epik beda masa sebagaimana dwilogi It buatan Andy Muschietti. Bukan mustahil Waktu Maghrib 2 mengambil inspirasi dari sana, tapi naskahnya luput menerapkan poin terpenting berupa eksplorasi karakter.
Karakter Adi luput digali. Sejauh mana trauma menghadapi teror Ummu Sibyan di masa kecil mempengaruhi tumbuh kembang serta kepribadian Adi, tak satu pun dipaparkan secara mendalam. Kedangkalan karakterisasi, ditambah minimnya eksplorasi terkait mitologi di balik sosok Ummu Sibyan, membuat Waktu Maghrib 2 cenderung melelahkan di beberapa titik.
Tapi tidak di saat Sidharta mulai memamerkan ciri khasnya. Modus operandi Ummu Sibyan yang tidak meneror korban secara langsung, melainkan mengendalikan pikiran anak-anak, berjasa menghindarkan film ini dari rangkaian jumpscare berisik, yang eksistensinya digantikan oleh kejar-kejaran dengan intensitas tinggi. Kreativitas tata kamera arahan Mandella Majid makin menguatkan ketegangan, kala Yugo jadi buronan rekan-rekan setimnya yang membekali diri dengan beragam senjata tajam. Andaikan intensitas tersebut mampu diterapkan pula di klimaksnya, yang seperti banyak horor lokal lain, seolah berlalu begitu saja.
Sidharta nampak bersenang-senang menjauhkan filmnya dari keklisean horor klenik, dengan membuat para antagonisnya lebih dekat ke arah zombie (serupa Zona Merah) atau segerombolan preman penyuka tawuran (Pertaruhan dan Ali Topan) alih-alih makhluk halus biasa. Selipan komedi yang "sangat tongkrongan Jogja" (digawangi trio Sadana Agung, Nopek Novian, dan Bagas Pratama Saputra), termasuk parodi sebuah video yang sempat viral beberapa waktu lalu, mungkin bakal memecah opini penonton, tapi sekali lagi, itu membuktikan keleluasaan sang sutradara untuk bersenang-senang.
REVIEW - THE ASSESSMENT
The Assessment tidak serta-merta menjabarkan dunianya. Apa yang terjadi pada Bumi? Mengapa langitnya terlihat aneh? Ke mana perginya orang-orang? Penilaian mengenai apa yang hendak diberikan terhadap protagonisnya? Kenapa tiba-tiba tulisan "Day 1" muncul di layar? Debut penyutradaraan Fleur Fortune ini adalah suguhan fiksi ilmiah yang selalu mencuatkan rasa penasaran di tiap langkahnya.
Aaryan (Himesh Patel) dan Mia (Elizabeth Olsen) adalah pasutri yang berbahagia. Mereka saling mencintai, sambil tetap menyibukkan diri dengan kegemaran masing-masing. Ketika Aaryan si profesor mendesain hewan virtual di ruang kerjanya, Mia mengurus tanaman di rumah kaca miliknya. Sederhananya, Aaryan hidup bersama kepalsuan teknologi, sedangkan Mia bertahan dengan realita.
Kini keduanya mendambakan kehadiran buah hati. Tapi memiliki anak di "dunia baru" ini merupakan perihal kompleks. Umat manusia mampu memperpanjang usia mereka berkat obat-obatan, namun sebagai gantinya, proses kelahiran dikontrol dengan begitu ketat. Aaryan dan Mia mesti melalui serangkaian tes terlebih dahulu, termasuk tinggal selama tujuh hari bersama Virginia (Alicia Vikander) yang akan menilai kesiapan keduanya.
Di malam pertama, Virginia berdiri dengan santai di depan pintu untuk mengamati Aaryan dan Mia berhubungan seks, seolah itu tindakan yang wajar. Semua sesuai peraturan. Hanya saja, peraturan tersebut enggan mempertimbangkan emosi mereka yang terlibat. The Assessment berlatar di dunia yang dibangun berdasarkan ketiadaan perasaan. Kekakuan yang juga diwakili oleh sinematografi dan tata artistiknya yang menghadirkan kesan dingin lewat pendekatan serba simetrisnya.
Penampilan Vikander mengingatkan pada peran yang membesarkan namanya di Ex Machina (2014) sebagai Ava si android. Virginia nampak dingin, kaku, tanpa perasaan layaknya robot, sebelum seiring waktu, secara perlahan, mulai memperlihatkan emosinya sebagai manusia. Jika Ava merupakan robot yang sengaja dibuat dengan banyak ciri manusia, maka Virginia adalah manusia yang dipaksa me-robot-kan dirinya.
Pada akhirnya manusia tetaplah manusia. Cinta, cemburu, trauma, nafsu, sakit, segala jenis rasa tersebut terlampau kaya untuk dipaksa tiada. Semakin besar kadar kemanusiaan coba ditekan dengan segala macam kepalsuan (sesempurna apa pun itu), semakin dekat pula kekacauan datang mengintai. Kekacauan yang acap kali disertai kejanggalan itu menjadi salah satu alasan The Assessment begitu menarik untuk diikuti.
Sesekali film ini tak lupa memamerkan daya tarik visual miliknya. Sebuah shot kala Virginia duduk di tengah hamparan lanskap, sementara dari kejauhan, di latar belakang, terlihat sekumpulan awan di langit menumpahkan air hujan, jadi salah satu contoh betapa menawannya pemakaian efek visual minimalis yang tepat guna.
Tapi bagaimana naskah buatan Dave Thomas, Nell Garfath-Cox dan John Donnelly mengolah elemen fiksi ilmiah menjadi tuturan tajam soal kemanusiaan tetap jadi amunisi utama. Konfrontasi di babak ketiga yang memberi kesempatan bagi Olsen dan Vikander untuk saling beradu akting, turut menegaskan pernyataan filmnya, bahwa penyebab semua rasa sakit yang karakternya rasakan adalah kegagalan sistem yang dipenuhi kebohongan dan kepalsuan. Jadi mana yang kalian pilih? Realita yang tak selamanya bahagia, atau kepalsuan yang terlihat indah?
(Prime Video)
REVIEW - ANGKARA MURKA
Di Angkara Murka, iblis dan dunia mistis bukanlah kekuatan independen yang menebar ancaman atas keinginan sendiri, melainkan sebatas alat yang dipakai oleh manusia berstatus penguasa lalim. Eden Junjung selaku sutradara sekaligus penulis naskah ingin menggambarkan bagaimana manusia bermata hijau jauh lebih jahat dan berbahaya daripada setan bermata merah menyala.
Latarnya adalah sebuah tambang pasir di sekitaran Merapi, di mana para buruh bekerja keras sehari penuh namun hanya menerima bayaran di bawah upah minimum. Didorong keinginan memperbaiki hidup, Jarot (Aksara Dena) mengajak rekannya, Bogel (Alex Suhendra), mencari permata yang konon banyak terkubur di balik sebuah bukit. Jarot pernah menemukan satu buah dan ingin memperoleh lebih banyak. Sejak itu Jarot menghilang secara misterius.
Buruh bernama Komar (Rukman Rosadi) pun menyimpan niat serupa dan mulai mengajak beberapa teman untuk mengikutinya. Di sisi lain, Ambar (Raihaanun), istri Jarot yang kini seorang diri mengurus putra mereka, coba mencari keberadaan sang suami dengan bekerja di tambang pasir tersebut.
Tidak seperti penyakit sederet horor Indonesia (Pabrik Gula dan KKN di Desa Penari misal), Angkara Murka tidak pelit memperlihatkan aktivitas di latarnya. Tambang pasirnya hidup, di mana penonton sering diajak mengamati rutinitas para buruh. Bahkan sangat sering, sampai film ini terjangkit penyakit lain berupa kemonotonan, akibat terlampau berkutat di satu lokasi, dengan situasi yang minim variasi.
Metode bercerita Angkara Murka pun sedikit janggal. Selama 89 menit durasinya, ia menerapkan tempo lambat khas horor alternatif yang enggan secara membabi buta menebar teror, namun di saat bersamaan, progresi narasinya justru terasa buru-buru. Naskahnya lemah dalam membangun transisi, penyutradaraannya kurang piawai menyusun build-up.
Satu departemen yang tak menyisakan keluhan adalah akting. Di luar nama-nama besar seperti Raihaanun (tampil solid walau memerankan karakter dangkal yang oleh naskahnya sebatas diberi penokohan "istri yang mencari suami") dan Rukman Rosadi, jajaran pemeran pendukung yang kebanyakan sudah lama berkecimpung di dunia teater Yogyakarta pun mampu memberikan kesan organik bagi karakter masing-masing.
Saya belum menyebut nama Whani Darmawan, sebab karakter Broto yang ia perankan perlu diberi sorotan khusus. Dialah pemilik lahan yang ditengarai menyimpan berlian, dan baru mengumumkan niatan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Disusun oleh pendekatan over-the-top dari sang aktor, Broto tidak merasa perlu menyembunyikan boroknya. Tatkala Ambar datang mencari Jarot, Broto dengan santainya menjawab, "Bojomu wes digondol demit".
Beberapa kali kita melihat penampakan makhluk misterius bertubuh hitam dengan mata merah menyala menyatroni mereka yang menyusup ke tambang berlian, tapi Broto-lah demit sesungguhnya. Dia tidak segan turun tangan membantai buruh tambangnya, (yang lebih layak disebut budak) tapi dampak paling mematikan yang ia bawa adalah, saat sikap sewenang-wenang dan kesenjangan sosial yang ia tanamkan berujung menciptakan siklus kekerasan yang menjadikan orang-orang lemah saling tikam hanya demi bertahan hidup.
Sungguh sayang, klimaks yang berpotensi melahirkan pertumpahan darah brutal di tengah pertarungan epik kala kaum akar rumput berjuang mendapatkan kesejahteraan mereka, berakhir canggung akibat kurang piawainya pengarahan Eden Junjung terhadap adegan-adegan bertempo tinggi. Setidaknya kita berkesempatan menyaksikan Whani Darmawan bertingkah liar bak makhluk barbar.
REVIEW - LILO & STITCH (2025)
Sebagaimana film orisinalnya yang rilis 23 tahun lalu, Lilo & Stitch versi live action masih memiliki kehangatan hasil dari olahan kisahnya mengenai nilai-nilai kekeluargaan. Tapi ada satu keping yang lenyap. Format live action membuat segalanya nampak lebih tertata, lebih normal, pula nihil anarki, walaupun elemen tersebut merupakan pondasi utama dari dinamika dua karakter titulernya.
Pola alurnya masih sama. Lilo (Maia Kealoha) adalah bocah 6 tahun asal Hawaii, yang sepeninggal orang tuanya, hidup di bawah asuhan sang kakak, Nani (Sydney Elizebeth Agudong). Lilo dengan segala hobinya, termasuk memungut umpan pancing untuk dijadikan gelang, dianggap aneh oleh teman-teman sepantarannya. Dia kesepian. Apalagi Nani, yang berjuang mempertahankan hak asuh atas adiknya, selalu sibuk bekerja.
Maia Kealoha yang melakoni debut aktingnya mampu membawakan sisi polos Lilo. Orang-orang mencapnya "nakal", tetapi ia sebatas bocah yang ingin menikmati kebocahannya. Sydney Agudong tidak sehijau lawan mainnya, namun inilah peran yang bakal melambungkan karirnya. Sebagai Nani, dia mudah disukai. Wajah lelah cenderung pasrah miliknya kala dihadapkan pada keliaran polah Lilo merupakan salah satu sumber kekuatan dari momen komedik film ini.
Di sisi galaksi yang lain, alien berbentuk seperti koala biru (Chris Sanders) yang dipanggil "Eksperimen 626" lahir dari hasil uji coba Dr. Jumba Jookiba (Zach Galifianakis). Dia liar, nakal, brutal, namun sebelum United Galactic Federation sempat mengasingkannya, si alien berhasil kabur ke Bumi. Di sanalah ia akan menjalin persahabatan dengan Lilo dan memperoleh nama barunya: Stitch.
Lilo adalah protagonis dengan motivasi yang begitu murni, yakni memiliki teman. Kemurnian itu memudahkan kita bersimpati padanya. Kedatangan Stitch memberinya rekan senasib. Keduanya diasingkan akibat dianggap aneh dan sukar dikendalikan. Alhasil, Lilo dan Stitch bisa bersahabat tanpa harus membohongi identitas masing-masing. Itulah mengapa, anarki yang menyusun dinamika mereka adalah poin substansial.
Format live action yang dipenuhi batasan berujung menekan keliaran eksplorasi. Hubungan Lilo dan Stitch hanya nampak seperti pertemanan biasa, antara bocah biasa dengan hewan peliharaan biasa yang sedikit nakal. Dean Fleischer Camp selaku sutradara hendak membawa pendekatan lebih membumi, yang justru berlawanan dengan esensi karya aslinya.
"You're not bad. You just do bad things sometimes", ucap Nani pada Lilo. Kelak, Lilo mengulangi nasihat serupa guna menghibur hati Stitch. Lilo & Stitch membawa pesan penting soal perlunya mewariskan nilai-nilai luhur dalam keluarga, yang diharapkan bakal selalu memupuk kebaikan tanpa pernah putus. Bukti bahwa naskahnya masih mempunyai materi mumpuni untuk menghangatkan hati.
Tapi tanpa dinamika berapi-api dua tokoh utamanya, yang mendominasi durasi adalah alur klise dengan bumbu humor generik, setingkat barisan sekuel medioker bagi animasi legendaris Disney yang rilis langsung ke DVD (Lilo & Stitch sendiri mempunyai tiga judul semacam itu). Kesan tersebut menguat kala inkonsistensi CGI-nya turut terpampang jelas. Sebuah shot kala Lilo duduk di mobil mainan nampak begitu "mengerikan".
Setidaknya tiada cela terkait tampilan Stitch, yang alih-alih coba memodifikasi, untungnya cenderung setia dalam hal desain, dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas. Stitch yang bukan lagi makhluk dua dimensi nampak lebih menggemaskan dengan ragam detail yang dipertajam, termasuk bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Terpenting, penonton dibuat percaya bahwa ia punya hati. Sebab poin itu merupakan aset terbesar di babak ketiganya.
Apa pun keluhan terhadap Lilo & Stitch bakal tereduksi oleh babak puncaknya yang menyentuh. Gambaran saat Stitch, dengan matanya yang menatap Lilo penuh kasih, memutuskan untuk menerima kematian seorang diri asalkan si sahabat dapat selamat, bagaikan "jawaban" dari film ini untuk "adegan insinerator" di Toy Story 3.
REVIEW - MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING
Entah berapa orang bisa secara menyeluruh memahami konflik milik Mission: Impossible - The Final Reckoning, yang notabene kelanjutan langsung dari Dead Reckoning (2023). Para pembuatnya sendiri menyadari keruwetan yang mereka ciptakan, sehingga menyelipkan rekap sebanyak mungkin di paruh awal. Tapi saya pikir tidak banyak penonton akan ambil pusing, karena filmnya mampu membangun kecemasan berbasis rasa percaya, bahwa jika sang protagonis gagal mengatasi kemustahilan dalam misinya, umat manusia bakal punah.
Ethan Hunt (Tom Cruise) bersama krunya yang kini diisi oleh Grace (Hayley Atwell), Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames), Paris (Pom Klementieff), dan Theo (Greg Tarzan Davis), masih berjuang memburu Gabriel (Esai Morales), dengan tujuan final menghentikan upaya kecerdasan buatan bernama Entity untuk menciptakan kiamat nuklir guna melenyapkan umat manusia. Masa depan coba diselamatkan, sambil sesekali mengunjungi masa lalu (baca: melempar rujukan terkait film-film sebelumnya) selaku cara memberi penghormatan bagi perjalanan panjang serinya.
Terdengar sederhana, namun praktiknya tentu sama sekali tidak. Tahap demi tahap berliku mesti dilalui Ethan dan tim, di mana dalam tiap titik, naskah hasil tulisan sang sutradara, Christopher McQuarrie, bersama Erik Jendresen, selalu menyediakan rintangan. Ethan tak dibiarkan bergerak barang sedikit saja tanpa ada usaha semesta untuk menghalanginya.
Maut setia mengintai, baik di darat, dasar samudera, hingga udara, tapi nyawa Ethan selalu selamat. Untunglah, sebab tiada yang dapat menyelamatkan dunia selain dia, setidaknya menurut para karakter film ini yang memposisikan Ethan bak mesiah. Berkali-kali pula mereka mengingatkan penonton betapa terancamnya dunia, saat satu demi satu hulu ledak nuklir jatuh ke tangan Entity.
Film ini tampil serius. The Final Reckoning bukanlah Ghost Protocol atau Rogue Nation yang masih punya banyak celah untuk penyegaran suasana. Di satu sisi, keseriusan tersebut mampu menyulut "sense of impending doom" yang membuat penonton harap-harap cemas menyaksikan aksi Ethan menghalangi kiamat. Tapi ada kalanya ia terlampau serius, bahkan di momen yang sejatinya konyol.
Salah satu yang paling sering terjadi adalah saat karakternya dibuat meneruskan kalimat eksposisi satu sama lain, yang menunjukkan ambisi McQuarrie membuat filmnya selalu terasa dramatis, termasuk dalam obrolan sederhana. Penanganan Fraser Taggart terhadap sinematografinya yang enggan membiarkan satu pun shot nampak generik turut mendukung ambisi sang sutradara.
Apakah dramatisasi hingga ke detail terkecil memang diperlukan? The Final Reckoning membuat protagonisnya terkurung di dalam kapal selam yang karam di dasar laut, pula bergelantungan di atas pesawat. Rasanya semua aksi menantang maut itu sudah cukup dramatis.
Membicarakan adegan aksi, di luar dugaan The Final Reckoning benar-benar menekan kuantitas untuk sepenuhnya fokus pada kualitas. Set piece besarnya cenderung minim, dan sebagai gantinya, McQuarrie memberi ruang bagi momen intens berskala kecil yang lebih kreatif, termasuk caranya mengakhiri ancaman Entity, yang meskipun jauh dari kesan masif, tetap mampu memaksa penonton menahan napas.
Sekalinya set piece besar itu datang, dia bukan hanya eksis untuk memenuhi durasi, tapi melahirkan pemandangan memukau yang akan terus diingat hingga bertahun-tahun lamanya. Ada kalanya rangkaian aksi tersebut berlangsung terlalu lama, namun menyaksikan usaha yang dicurahkan, keengganan McQuarrie untuk memangkas durasi sejatinya bisa dipahami.
Tengok saja saat Ethan memasuki kapal selam Sevastopol yang bersemayam di dasar samudera. Set piece itu seolah menolak untuk berakhir, sembari terus melemparkan batu sandungan bagi si jagoan. Apakah membosankan? Jelas tidak. Atmosfer mencekam yang dibangun, pencapaian teknis dalam detik demi detiknya, pula keputusan untuk (hampir) meniadakan tuturan verbal agar menguatkan nuansa imersif, semuanya mengagumkan.
Menyaksikan Tom Cruise bergelantungan di atas pesawat dwisayap yang melayang tinggi, kekaguman terhadap filmnya sekaligus sang aktor pun mencapai titik tertinggi. Apakah The Final Reckoning merupakan salam perpisahan? Entahlah. Filmnya nampak ragu-ragu menegaskan status tersebut. Tapi pada era di mana kepalsuan digital dalam bentuk AI semakin meresahkan, Tom Cruise lewat aksi gilanya yang "serba nyata" merupakan wujud perlawanan yang kehadirannya bakal selalu diterima.
REVIEW - MUNGKIN KITA PERLU WAKTU
Mungkin Kita Perlu Waktu dibuka saat seorang remaja berbaring sembari menyalakan lalu mematikan lampu kamarnya secara berulang. Setiap lampu padam, nampak sekelebat pemandangan mengenai kecelakaan yang merenggut nyawa kakak perempuannya di suatu malam. Karya terbaru Teddy Soeriaatmadja ini membicarakan hal-hal yang manusia lihat serta rasakan kala jatuh dalam jurang terkelam kehidupan. Menyeramkan, menyakitkan, tapi bagian terburuknya, semua itu tak dapat dihapus semudah mengusir kegelapan yang hanya membutuhkan secercah cahaya lampu.
Selepas alunan Nocturnes, Opus 9 gubahan Chopin yang bakal berulang kali diperdengarkan termasuk dalam versi gitar akustik, kita pun diajak berkenalan lebih jauh dengan sosok si remaja beserta keluarganya. Namanya Ombak (Bima Azriel). Dia terjebak depresi pasca kematian kakaknya, Sara (Naura Hakim). Ombak merasa bersalah, karena dialah yang menyetir mobil pada kecelakaan yang merenggut nyawa Sara.
Kondisi orang tuanya tidak lebih baik. Sang ibu, Kasih (Sha Ine Febriyanti), berupaya mencari ketenangan lewat agama. Ombak yang sempat mencoba bunuh diri dibawanya ke ahli rukiah. Dia pun hendak berangkat umrah bersama sang suami, Restu (Lukman Sardi). Keterpurukan Kasih, yang bahkan terkesan menjauhi Ombak, sejatinya dapat dipahami. Sebagai ibu religius, tentu ia merasa terpukul mendapati putrinya meninggal dalam kondisi mabuk.
Sebaliknya, Restu berusaha terlihat tabah, karena sebagai kepala keluarga ia merasa bertanggung jawab supaya "kapal" yang mereka naiki tidak karam. Situasi apa pun ia sikapi secara santai, yang justru tak jarang memberi luka tambahan bagi istri maupun anaknya. Singkatnya, tiga anggota keluarga disfungsional ini menjalani hidup tanpa hasrat. Mereka cuma menjalankan peran sosial masing-masing layaknya bagian-bagian penggerak dalam sebuah mesin.
Pendekatan yang Teddy pakai guna menangani isu kesehatan mentalnya cenderung sensitif. Kepiluan tiap karakter bukan dipakai sebagai pemantik dramatisasi, tangisan mereka (yang tidak mengisi layar tiap lima menit sekali) pun tidak dieksploitasi. Dampak emosi bukan lahir dari manipulasi, melainkan akting heartbreaking trio pemeran utamanya. Entah ledakan-ledakan rasa dari Bima Azriel, kata-kata tajam yang menyimpan luka dari Sha Ine Febriyanti, atau tatapan menusuk Lukman Sardi yang berjuang keras menahan letupan pilunya.
Mungkin Kita Perlu Waktu mengedepankan proses observasi terhadap interaksi individu, baik dengan individu lain maupun hatinya sendiri. Tengok saat Ombak akhirnya bisa mengobrol dengan Aleiqa (Tissa Biani), teman sekelas yang selama ini diam-diam ia taksir, dan berujung saling berbagi sisi gelap satu sama lain. Cara Teddy mengemas dinamika keduanya serasa berkiblat pada metode Richard Linklater di Before Sunrise (termasuk menyertakan adegan music booth) yang menjadikan obrolan selaku jendela mengamati ruang intim manusia.
Filmnya bakal jauh lebih kuat andai Teddy memberi jatah lebih bagi hubungan dua remaja tersebut, alih-alih mengharuskannya berbagi porsi dengan momen kunjungan Ombak ke Nana (Asri Welas), psikolog yang direkomendasikan oleh ayahnya. Masalahnya, penggambaran Teddy terhadap si psikolog cenderung ambigu.
Nana bersikap ketus, minim empati, pula terkesan menghakimi kala mendengarkan konsultasi Ombak. Dia mewakili segala hal yang keliru dalam kode etik seorang psikolog. Tapi ada kalanya ia memberi pesan bermanfaat, termasuk di adegan konsultasi terakhir Ombak, maupun obrolannya dengan Restu. Apakah Teddy memang hendak memberi gambaran soal psikolog yang buruk, atau malah kita sedang melihat contoh penanganan (penulisan, penyutradaraan, akting) yang buruk terhadap sesosok karakter? Tidak pernah jelas.
Sungguh sayang jika perjalanan Mungkin Kita Perlu Waktu menemui batu sandungan dalam bentuk karakter minor dengan signifikansi minim seperti Nana, tapi alurnya terlampau menarik untuk bisa diruntuhkan begitu saja. Daripada membaik secara bertahap layaknya di film-film arus utama, seiring durasi, kita justru melihat kondisi para protagonisnya yang semakin jatuh.
Konklusinya pun menolak bermain aman. Teddy bersedia berpijak pada realita dan menggunakan sudut pandang yang tak harus sejalan dengan norma standar masyarakat. Karena ada kalanya sebuah kapal memang sudah terlalu banyak mengalami kerusakan, dan bakal membahayakan penumpangnya bila dipaksa terus mengapung. Mungkin itulah waktunya para kru lanjut berlayar dengan kapal baru masing-masing.
REVIEW - THE RED ENVELOPE
The Red Envelope menawarkan konklusi hangat yang menunjukkan bahwa pernikahan seperti apa pun, baik gay atau hetero, secara esensial adalah penggabungan dua keluarga. Sebuah proses menambah orang yang kita sayang sekaligus menyayangi kita. Poin itulah yang mestinya dieksplorasi lebih jauh dan dijadikan menu utama oleh karya terbaru Chayanop Boonprakob (Friend Zone, May Who?, SuckSeed) ini.
Sayang, durasi cukup panjang (125 menit) milik remake dari Marry My Dead Body yang sempat mewakili Taiwan di Academy Award 2024 ini tak dimanfaatkan guna menguatkan penceritaan. Isu pernikahan sesama jenis yang telah dilegalkan sejak awal 2025 bukannya diperdalam, malah sebatas dijadikan pernak-pernik humor.
Protagonis kita adalah Menn (Putthipong Assaratanakul), informan kepolisian yang tak kompeten dalam bekerja, sedangkan isi pikirannya cuma dipenuhi keinginan memikat seorang petugas bernama Goi (Arachaporn Pokinpakorn). Sampai ia memungut sebuah amplop merah yang tanpa diduga membuatnya mesti melangsungkan pernikahan gaib dengan arwah Titi (Krit Amnuaydechkorn).
Titi meninggal akibat kecelakaan sebelum sempat menikah, dan sang nenek (Piyamas Monyakul) ingin mewujudkan impian tersebut. Masalahnya Titi merupakan seorang gay, sehingga keinginannya tak pernah direstui oleh ayahnya (Teravat Anuvatudom). Sampai di sini, The Red Envelope punya segalanya untuk menghadirkan kisah dengan daya hibur serta dampak emosi tinggi.
Di awal pertemuan mereka, Menn takut pada Titi. Bukan semata disebabkan ia hantu, pula karena orientasi seksualnya. Menn jijik pada sesuatu yang asing baginya. Di lain pihak, Titi ingin orang-orang seperti Menn tidak segampang itu menghakimi dirinya tanpa mengenal secara lebih mendalam.
Naskah yang ditulis oleh sang sutradara, Chayanop Boonprakob, bersama Thamsatid Charoenrittichai, Chantavit Dhanasevi, dan Weawwan Hongvivatana, sejatinya mampu menciptakan perjalanan menyenangkan, namun di saat bersamaan, gaya bertutur alurnya tak mendukung dinamika kompleks antar dua tokoh utamanya sebagaimana dijabarkan di atas.
Alurnya menyoroti penyelidikan mengenai kebenaran di balik kematian Titi, yang skalanya seketika membesar hingga membenturkan dua protagonisnya dengan skema licik seorang bandar narkoba kelas kakap. Chayanop menggulirkan kisah tersebut dengan cepat guna menjaga kesan menghibur (yang mana berhasil), walau secara bersamaan, alur yang bergerak terlampau liar cenderung menyulitkan terjalinnya kepedulian serta koneksi emosional antara karakter dan penonton.
The Red Envelope hadir dengan humor yang tidak jauh-jauh dari nuansa nakal, seolah tuturan mengenai LGBTQ harus selalu kental banyolan jorok. Beberapa humor usang masih dipresentasikan (adegan "mengocok minuman" bahkan muncul lebih dari sekali), walau untungnya, tatkala kreativitas para penulis tengah mencuat, kenakalan tersebut tetap efektif memancing tawa tak terduga. Apalagi dua pelakon utamanya, Putthipong Assaratanakul dan Krit Amnuaydechkorn, sama-sama tampil apik perihal menyeimbangkan keseriusan akting dramatik dan kekonyolan komedik.
Mungkin The Red Envelope belum berhasil memaksimalkan potensinya. Cukup disayangkan, mengingat tahun lalu GDH pernah melahirkan kisah LGBTQ dengan sensitivitas lebih tinggi lewat The Paradise of Thorns. Tapi bukan berarti relevansinya berkurang. Melihat cara LSF mencederai film ini, termasuk kala memotong adegan battle dance yang bahkan bukan "gay thing", atau ketika mendesain terjemahan supaya terkesan "tidak terlalu homoseksual", The Red Envelope justru semakin penting untuk disaksikan.
REVIEW - FINAL DESTINATION BLOODLINES
Seperempat abad lalu, Final Destination memodifikasi formula DMT (Dead Teenager Movies) dengan menjadikan kematian selaku antagonis, alih-alih memakai pembunuh bertopeng atau monster sebagai perantara guna mencabut nyawa. Sekarang keunikan itu telah menghasilkan keklisean sendiri, dan seperti putaran roda takdir yang kembali ke titik awal, Final Destination Bloodlines datang membawa perubahan (lagi). Bukan secara radikal, namun untuk kali pertama, seri ini bersedia menyelami mitologinya.
Pada tahun 1968, Iris (Brec Bassinger) dan kekasihnya, Paul (Max Lloyd-Jones), terjebak dalam kecelakaan mematikan di atas menara pencakar langit. Alih-alih hanya firasat yang Iris dapatkan sebagaimana adegan pembuka film-film sebelumnya, tragedi tersebut adalah mimpi buruk yang selama dua bulan terakhir dialami Stefani (Kaitlyn Santa Juana). Barulah Stefani sadar bahwa gadis dalam mimpinya adalah sang nenek (Gabrielle Rose) yang kini hidup sendirian mengasingkan diri dan dianggap gila oleh keluarganya.
Selama puluhan tahun, Iris menghindari mempelajari pola dan taktik sang maut untuk menghindari kejarannya. Iris percaya bahwa ia semestinya tewas dalam peristiwa tahun 1968, yang berarti seluruh keturunannya pun tidak semestinya eksis, dan kematian berusaha mencabut nyawa mereka semua. Ingat, kematian amat benci bila suratan takdirnya dicurangi.
Karakter Final Destination Bloodlines masih didominasi muda-mudi. Ada Charlie (Teo Briones), adik Stefani, pula tiga sepupu mereka, Erik (Richard Harmon), Bobby (Owen Patrick Joyner), dan Julia (Anna Lore). Tapi Stefani pun mesti menyelamatkan beberapa orang dewasa, mulai dari pamannya, Howard (Alex Zahara), juga sang ibu, Darlene (Rya Kihlstedt), yang telah lama pergi dari kehidupannya.
Naskah buatan Guy Busick dan Lori Evans Taylor menggeser lingkupnya dari lingkaran pertemanan remaja ke ranah keluarga, sehingga melahirkan judul Final Destination paling emosional. Setiap karakter memiliki motivasi kuat untuk menyelamatkan karakter lain. Erik menjadi salah satu karakter paling likeable sepanjang sejarah serinya karena faktor tersebut. Sekilas perangainya penuh ketidakpedulian, namun dialah yang berjuang paling keras mengakali upaya maut menjemput keluarganya.
Butuh waktu sampai gagasannya menemui sasaran, namun setelah Bloodlines menampakkan keunikannya dengan menggali lebih dalam konsep soal "dikejar maut" yang nantinya secara subtil menjelaskan segala peristiwa di lima film pertama, daya hiburnya tak lagi bisa dibendung.
Deretan kematiannya dieksekusi secara brutal. Mungkin tak ada yang bakal menancapkan trauma seperti adegan truk di Final Destination 2, maupun mengundang kecemasan luar biasa sebagaimana Final Destination 5 dengan latihan gimnastiknya, namun tiap nyawa yang terenggut dieksekusi dengan sadisme penuh energi duo sutradaranya, Zach Lipovsky dan Adam Stein.
Proses menebak-nebak dari mana datangnya sumber bahaya juga tampil semakin menyenangkan, pula semakin rumit, yang bak menunjukkan keusilan sang maut. Ya, kematian nampak bersenang-senang di sini, layaknya predator yang bermain-main dengan mangsa sebelum menerkamnya, sembari mendengarkan lagu-lagu populer seperti Without You.
Mungkin memang benar bahwa kematian punya selera humor yang sinting. Filmnya sendiri menanam lebih banyak komedi, seiring pendekatannya yang cenderung self-aware. Daripada menutupi, Bloodlines justru dengan sengaja menerapkan berbagai kekonyolan di alurnya, lalu mengajak penonton menertawakannya bersama-sama.
Film ini sadar bahwa seri Final Destination dengan segala rules anehnya bukan sesuatu yang perlu dipandang serius, kemudian memilih mengakuinya dengan bangga dan menjadikannya lelucon alih-alih menutupinya. Saya bisa membayangkan apabila dilanjutkan di masa depan, seri ini bisa saja menempuh jalur serupa Scream, di mana karakternya belajar mencurangi kematian dengan cara menonton film-film Final Destination.
Tapi bukankah hampir semua upaya kabur dari maut di Final Destination berujung kegagalan? Betul. Mungkin karena itulah kita mesti mencermati ucapan William Bludworth (Tony Todd), yang kali ini kemunculannya memiliki signifikansi lebih terkait mitologinya. Melalui adegan yang seolah jadi salam perpisahan sempurna nan mengharukan bagi Tony Todd sebelum meninggal akhir tahun lalu, Bludworth menasihati karakternya, bahwa alih-alih menghabiskan waktu dengan terus-menerus lari, bukankah sebaiknya waktu itu dimanfaatkan untuk menikmati hidup sebaik-baiknya?
REVIEW - WARFARE
Pertama kali penonton diajak bertemu tentara Amerika di film ini, mereka sedang menonton video aerobik dengan luar biasa bersemangat bak tengah berpesta pora. Itu pula kali terakhir kita melihat semangat mereka. Warfare bukan soal keseruan merenggut nyawa musuh di medan perang, melainkan ketegangan dari upaya mempertahankan nyawa. Ketimbang ode untuk patriotisme, ia lebih seperti elegi sarat penyesalan.
Alex Garland menulis sekaligus menyutradarai filmnya bersama Ray Mendoza, mantan anggota Navy SEALs yang di sini menuturkan pengalamannya kala bertugas di Perang Irak. Pada 19 November 2006, Mendoza (versi film diperankan oleh D'Pharaoh Woon-A-Tai) dan peletonnya dikirim untuk melakukan pengintaian guna mendukung operasi dari korps marinir.
Di tengah kegelapan malam, Erik (Will Poulter) memimpin pasukannya menuju sebuah rumah yang bakal dijadikan basis pengintaian. Rumah dua tingkat itu dihuni pula oleh dua keluarga sipil. Penghuni lantai atas cuma bisa pasrah menyaksikan tembok rumah dijebol dan diobrak-abrik untuk dijadikan markas sementara. Garland dan Mendoza menolak menutup mata bahwa apa yang pasukan Amerika lakukan adalah penjajahan terhadap orang-orang tak bersalah.
Dua penerjemah, Farid (Nathan Altai) dan Noor (Donya Hussen), turut serta dalam operasi. Mereka cenderung diperlakukan semena-mena, termasuk diperintahkan untuk menjadi tameng di baris terdepan kala bahaya menghampiri. Tatkala Farid tewas mengenaskan dengan tubuh yang terburai, namanya luput disertakan dalam kelompok "korban jiwa", seolah eksistensinya sama sekali tidak berharga.
Warfare enggan memberi penokohan mendalam mungkin karena para pembuatnya tidak ingin penonton mengalami bias dalam proses observasi. Tatkala misi mulai berantakan pun kita tidak digiring untuk bersimpati pada penderitaan yang dialami peleton Mendoza. Jikalau muncul simpati, atau minimal rasa pilu menyaksikan luka-luka mengenaskan yang dialami karakternya, itu adalah respon natural kita selaku manusia saat dihadapkan pada tragedi.
Dipaparkan secara real time sepanjang 95 menit, paruh awalnya menegaskan tujuan Warfare untuk mengedepankan tangkapan realita dan paparan prosedural ketimbang dramatisasi. Realitanya, misi pengintaian bukan aktivitas yang mengasyikkan. Alih-alih terlibat baku tembak seru, si penembak jitu mesti "mematung" selama berjam-jam sembari mencatat situasi. Anggota lain pun disibukkan oleh rutinitas membosankan yang sama.
Tengok pula saat lesatan peluru mulai memperlihatkan ancamannya. Para Navy SEALs tidak bisa segampang itu melarikan diri. Setumpuk peralatan militer yang tersebar di penjuru rumah wajib dikumpulkan dahulu sebelum dilakukan evakuasi, yang mana meningkatkan risiko ancaman.
Bertepatan dengan fase di saat karakternya terjebak tak berdaya di dalam rumah, alurnya sempat mengalami stagnasi. Untungnya intensitas senantiasa bisa dijaga oleh duo sutradara, pula departemen tata suara yang begitu efektif mengolah atmosfer mencekam. Dentuman-dentuman bomnya memang terdengar bombastis, tapi teriakan manusia yang tak henti mengiris telinga nyatanya jauh lebih mengguncang. Kemudian saat suara-suara itu akhirnya memudar, bukan patriotisme yang terasa. Hanya ada keheningan yang merekam jejak-jejak penderitaan.
REVIEW - SAYAP-SAYAP PATAH 2: OLIVIA
Serupa film pertamanya, Sayap-Sayap Patah 2: Olivia hanya dilandasi satu tujuan: membuat penonton terisak menyaksikan tragedi akibat aksi terorisme. Tiada ruang bagi kompleksitas manusia maupun eksplorasi mendalam terkait isu radikalisme. Setidaknya, sebagai tearjerker sederhana ia bekerja dengan baik terutama di babak akhir.
Mengambil inspirasi dari peristiwa "Bom Samarinda 2016", sepak terjang anggota kepolisian di bawah pimpinan Sadikin (Nugie) kembali jadi sorotan. Kini giliran Pandu (Arya Saloka) yang kita ikuti kesehariannya. Pandu yang setahun lalu kehilangan istrinya karena suatu penyakit, kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga kerap meninggalkan sang putri, Olivia (Myesha Lin), tinggal berdua di rumah bersama neneknya (Meriam Bellina).
Arya Saloka mampu menghidupkan figur ayah penyayang sehingga mudah memancing simpati penonton. Piawai pula ia membangun chemistry bersama para pelakon lain, dari hubungan ayah-anak hangat dengan si kecil Myesha Lin, hingga romantisme antara Pandu dan Suri (Dara Saraswati), guru Olivia.
Sampai tiba waktunya bagi Leong (Iwa K) selaku pelaku penyerangan Mako Brimob untuk bebas dari penjara. Bagaimana mungkin pentolan teroris yang aksinya menyebabkan kematian anggota polisi bebas sedemikian cepat, tatkala di dunia nyata, para pelakunya dijatuhi hukuman mati? Perlu kadar suspension of disbelief yang cukup tinggi supaya kita dapat menerima poin cerita tersebut, tapi intinya Leong kembali ke masyarakat dan tinggal bersama anaknya, Askar (Bio One).
Naskah buatan Jocelyn Coroelia dan Rahabi Mandra sempat menyulut dinamika menarik tatkala dinamika rumit antara Leong dan Askar mengisi layar. Askar membenci tindakan ayahnya, sedangkan Leong nampak ingin meyakinkan si putra tunggal bahwa ia telah berubah. Kali ini Iwa K tak hanya mengumbar kengerian, pula kompleksitas seorang ayah yang terpecah antara ideologi dan kasih sayang terhadap anak. Tercipta komparasi antara Pandu dan Leong, sebagai dua sosok ayah yang sama-sama tidak pernah hadir di dekat buah hati mereka. Menarik. Kompleks.
Sayangnya kompleksitas tersebut tak bertahan lama. Begitu Leong kembali menempuh jalur radikalisme selepas disambangi oleh Wabil (Muhammad Khan), tuturannya kembali ke "setelan pabrik" yang amat hitam putih. Padahal pilihan menggambarkan sosok teroris sebagai manusia biasa alih-alih entitas asing nan menyeramkan justru akan mengerdilkan sepak terjang mereka dan bukan membenarkannya.
Jadi, poin apa yang sejatinya Sayap-Sayap Patah 2: Olivia ingin sampaikan dari dinamika tokoh-tokohnya? Entahlah. Sebab memasuki paruh akhir, komparasinya berpindah kepada duo Pandu-Askar, sehingga semakin mengaburkan poin yang hendak filmnya tekankan.
Selepas melalui proses sarat stagnasi, saat sorotan terhadap kehidupan keluarga Pandu luput menambah bobot narasi akibat presentasi yang repetitif, kita tiba di babak final yang jadi amunisi utama filmnya. Tersebar banyak lubang narasi di sepanjang perjalanan menuju ke sana (Sadikin yang lebih masuk akal dijadikan target utama teroris ketimbang Pandu, antagonis yang bisa sedemikian mudah menyamar menjadi kru acara, dll.), tapi kemampuan Ferry Pei Irawan selaku sutradara dalam mengkreasi tragedi menyesakkan di layar bisa menebus berbagai kelemahan tersebut.
Dibanding film pertama yang terkesan instan dan setengah matang, klimaks Sayap-Sayap Patah 2: Olivia jauh lebih menusuk hati, baik karena visualisasi eksplisit yang bisa jadi bakal terasa traumatis dari sang sutradara, hingga kemampuan para pemainnya, terutama Arya Saloka dan Meriam Bellina, untuk mencabik-cabik perasaan penonton lewat akting mereka.
Sekali lagi, jangan mengharapkan eksplorasi kompleks mengenai isu radikalisme. Keputusan filmnya mengubah salah satu karakternya menjadi figur kejam akibat dendam, tanpa mengajak penonton menelisik secara lebih dalam, menandakan kegagalan naskahnya membuka mata atas keburukan sistem yang turut berkontribusi memperkeruh situasi (setidaknya menunjukkan keengganan membagi porsi kesalahan secara adil). Tapi jika sebatas ingin menumpahkan air mata karena kisah tragisnya, Sayap-Sayap Patah 2: Olivia bakal memenuhi itu.
REVIEW - HOLY NIGHT: DEMON HUNTERS
"Karena tidak ada lagi penjahat yang mampu menahan tinju mautnya, kini giliran para iblis yang jadi target bogem mentah Ma Dong-seok". Lelucon ini banyak orang-orang lontarkan pasca mengetahui proyek baru dari salah satu leading man terbesar sinema Korea Selatan tersebut. Holy Night: Demon Hunters pun seolah dibangun berdasarkan lelucon di atas, yang sejatinya merupakan premis menarik. Sayang, para pembuatnya bak kebingungan mesti mengembangkannya ke arah mana.
Ma Dong-seok memerankan Bau, yang menjalankan perusahaan penyedia jasa pengusiran setan bersama dua karyawannya, Sharon (Seohyun) dan Kim Gun (Lee David). Modus operandi mereka sebagai berikut: Sharon si pemilik kekuatan sakti bertugas melakukan eksorsis, Bau memukuli para pemuja setan yang menurut mitologi film ini selalu berada di sekitar korban kesurupan, sedangkan Kim merekam jalannya ritual.
Bahkan di ranah paling mendasar (penokohan) naskah buatan sang sutradara, Lim Dae-hee, sudah hilang arah. Entah apa fungsi rekaman yang Kim tangkap, sebab para protagonisnya sendiri tak pernah meninjau ulang maupun menjadikannya media untuk memasarkan bisnis mereka. Interaksi menggelitik coba dipakai guna membangun hubungan ketiga karakter utama, tapi eksekusi humornya begitu lemah. Timing-nya kerap meleset, pun presentasinya penuh keragu-raguan, seolah sang sineas khawatir filmnya tampil terlampau konyol.
Misi teranyar mereka datang dari permintaan dokter neuropsikiatri bernama Jung-won (Kyung Soo-jin), yang curiga bahwa kondisi sang adik, Eun-seo (Jung Ji-so), bukan disebabkan penyakit klinis namun gangguan klenik. Naskahnya berusaha memancing simpati penonton terhadap Jung-won, tapi masalahnya, penokohannya luar biasa menyebalkan. Si dokter cerdas lebih banyak berteriak, menangis, pula gampang dimanipulasi oleh iblis sehingga acap kali melakukan tindakan luar biasa bodoh.
Menonton Holy Night: Demon Hunters ibarat sedang menyaksikan kompilasi dari seluruh trik klise dalam katalog horor eksorsisme, yang terkesan asal disatukan akibat Lim Dae-hee masih kurang percaya diri dalam debut penyutradaraannya ini. Kemampuannya mengolah pacing kala mengarahkan adegan eksorsisme pun layak dipertanyakan. Proses pengusiran setan yang mestinya sarat intensitas justru berujung minim energi, biarpun sudah didukung totalitas Seohyun yang mengerahkan segala daya upayanya.
Menyebut film yang dibintangi Ma Dong-seok "minim energi" memang terasa janggal, namun demikianlah adanya Holy Night: Demon Hunters. Seperti biasa, tiap tinju si jagoan dibarengi efek suara eksplosif layaknya lesatan peluru shotgun, tapi sang sutradara nampak masih belum menguasai cara memaksimalkan daya bunuh dari bogem mentah sang aktor yang turut merangkap produser tersebut.
Jika ada yang patut diapresiasi, itu adalah kesediaan naskahnya memberi sisi rapuh pada karakter Bau. Berbeda dengan figur tanpa tanding yang Ma Dong-seok perankan di judul-judul populernya belakangan ini, Bau menyimpan segudang rasa takut akibat trauma yang berasal dari tragedi masa lalunya.
Memasuki babak final, Holy Night: Demon Hunters mendadak memberi kekuatan tambahan bagi Bau, yang meski memunculkan kesan "semau sendiri" dari naskahnya, berujung menghadiahkan momen epik di momen puncaknya, kala Ma Dong-seok, setelah menghabiskan 90 menit menghajar gerombolan penjahat kelas teri, akhirnya secara literal memukul iblis sampai terlempar ke neraka. Andai momen itu datang jauh lebih awal.
REVIEW - KNEECAP
Haruskah perlawanan terkesan serius dan kelam? Apakah kekakuan wajib dikedepankan dan berjalan beriringan dengan keberhasilan perjuangan? Kneecap, trio hip hop asal Belfast, jelas menolak berpikir demikian. Sehingga biopic yang mendramatisasi perjalanan karir mereka ini pun dipresentasikan sebagai "film perlawanan" yang menyenangkan.
Naskah buatan sang sutradara, Rich Peppiatt, mengawali narasinya dengan berkelakar mengenai tendensi film Irlandia untuk membuka kisahnya dengan gambaran-gambaran kerusuhan, maupun tragedi seperti peristiwa Minggu Berdarah tahun 1972. Kneecap berbeda.
Pertama kali penonton diajak berkenalan dengan Liam Óg Ó hAnnaidh dan Naoise Ó Cairealláin (memerankan diri sendiri) selepas mereka dewasa, kedua protagonis kita tersebut sedang berpesta di tengah hutan sembari dikuasai pengaruh ketamin yang menghadirkan halusinasi liar. Dilihat sekilas, mereka tidak cocok menjadi ikon perlawanan. Begitu pula JJ Ó Dochartaigh yang menjalani rutinitas membosankan selaku guru musik.
Sedikit fakta menarik tentang tiga laki-laki di atas. Ayah Naoise yang juga akrab dengan Liam sedari kecil, Arlo (Michael Fassbender), merupakan anggota paramiliter yang disegani, sebelum suatu hari memilih memalsukan kematiannya guna menghindari kejaran otoritas. Sedangkan kekasih JJ, Caitlin (Fionnuala Flaherty), termasuk pentolan dalam gerakan untuk memperjuangkan supaya Bahasa Irlandia diakui secara resmi, pula bebas digunakan secara kasual alih-alih dipandang sebagai simbol pemberontakan.
Intinya, pergerakan, perlawanan, atau apa pun sebutannya, amat dekat dengan kehidupan mereka bertiga. Sampai suatu ketika, berkat campur tangan takdir, JJ menemukan buku catatan berisi lirik lagu dalam Bahasa Irlandia yang ditulis oleh Liam. Seketika tercetus ide untuk menggubah barisan lirik tersebut menjadi lagu rap.
Sebelumnya kita tak pernah melihat Liam dan Naoise menembakkan rima dari mulut mereka, namun ketika tiba waktunya merekam musik, keduanya mendadak terdengar seperti anggota N.W.A. di masa keemasannya. Lubang narasi ala film biografi arus utama semacam itu termasuk babak ketiga yang berlangsung terlampau dramatis karena naskahnya memaksa untuk memberi resolusi bagi seluruh konflik di waktu bersamaan kadang masih jadi batu sandungan, namun energi yang disuntikkan oleh Rich Peppiatt beserta tiga pemeran utamanya membuat film ini terasa spesial.
Diiringi lagu-lagu Kneecap yang eksplosif serta tidak ragu melempar kritik terhadap penindasan oleh pihak Britania, sembari tanpa malu-malu membicarakan hedonisme sarat kokain, filmnya membuktikan bahwa perlawanan tak harus mengalienasi kesenangan. Mereka berpesta, teler bersama di tengah proses pembuatan lagu yang berlangsung liar, pernah pula mengacaukan jalannya Orange walk dalam adegan kejar-kejaran seru yang dihiasi lagu Smack My Bitch Up kepunyaan The Prodigy.
Pasca salah satu lagunya berhasil viral, Kneecap langsung mengguncang seisi bangsa. Pemerintah Britania memandang karya mereka sebagai bentuk anarki, sementara kaum konservatif dari organisasi paramiliter bernama RRAD (Radical Republican Against Drugs), yang merupakan parodi dari kelompok dunia nyata bernama RAAD (Republican Action Against Drugs) mengutuk gaya hidup mereka yang dipenuhi narkoba.
Bahkan di satu titik, Caitlin mengeluhkan sepak terjang Kneecap yang menurutnya mengganggu usaha memperjuangkan hak berbahasa. Arlo yang menyebut pelariannya sebagai "misi" dan amat mengagungkan metode konservatifnya pun mengecam tindakan sang anak. Apakah perjuangan mesti disuarakan dalam satu nada yang sama?
Menariknya, trio Kneecap tidak pernah berniat memposisikan diri sebagai pejuang hak asasi. Barisan lirik kritis mereka bukan hasil rumusan yang disusun matang-matang demi tujuan tertentu, melainkan sebatas teriakan isi hati. Semuanya terjadi secara alami. Para personil Kneecap cuma mau bersenang-senang, sambil secara bebas menulis, bernyanyi, dan mengatakan apa pun yang diinginkan. Mereka hanya ingin bicara.
(Klik Film)
REVIEW - MENDADAK DANGDUT
Mendadak Dangdut orisinal (2006) adalah proses mengenali akar rumput, di mana si protagonis dipaksa keluar dari dunia fantasi gemerlap miliknya, untuk menyambangi realita yang diwakili oleh semangat musik dangdut. Skena dangdut benar-benar coba diresapi esensinya. Mendadak Dangdut versi baru melupakan semua esensi itu, lalu sebatas tampil layaknya seorang musisi pop yang meng-cover lagu dangdut secara asal-asalan tanpa berusaha mengenalinya.
Disutradarai oleh penulis film pertamanya, Monty Tiwa (turut menulis naskahnya lagi bersama Erik Tiwa dan Muttaqiena Imaamaa), ketimbang sekuel atau remake, Mendadak Dangdut lebih dekat ke ranah rekuel, dengan mengambil latar di semesta yang sama, namun dengan karakter serta konflik yang sama sekali berbeda.
Sesungguhnya ia diawali dengan meyakinkan. Naya (Anya Geraldine) si bintang pop ternama mendadak terbangun di sebelah mayat yang berlumuran darah. Tidak yakin mengenai apa yang terjadi, Naya yang dicurigai sebagai pembunuhnya pun mengajak sang adik, Laura (Aisha Nurra Datau), kabur sejenak untuk menyusun strategi. Karena kondisi, ayah mereka (Joshua Pandelaki) yang menderita alzheimer pun terpaksa ikut serta.
Keputusan Naya untuk kabur lebih masuk akal dibanding pilihan yang diambil Petris (Titi Kamal) dan Yulia (Kinaryosih) di film pertama. Pasalnya situasi yang dialami jauh lebih menyudutkan, pun Naya bukan semata-mata lari tanpa tujuan. Tapi hanya sampai sini saja keunggulan milik versi barunya.
Pertemuan dengan Wawan (Keanu AGL) dan Wendhoy (Fajar Nugra) yang sedang merintis orkes mereka seketika membawa perjalanan hidup Naya ke arah tak terduga. Naya si musisi pop yang terbiasa membawakan lagu-lagu lirih ditemani gitarnya kini mesti belajar mengolah cengkok dalam bernyanyi sembari bergoyang mengikuti kemeriahan alunan nada. Well, seharusnya itulah yang terjadi.
Naskah Mendadak Dangdut punya satu lubang besar: Naya tidak melalui proses belajar. Tanpa tuntunan dari siapa pun, mendadak ia langsung memahami cara mengubah gaya bernyanyinya. Jika dahulu Petris mesti melewati jalan panjang untuk bisa mengapresiasi musik dangdut, di sini Monty meniadakan proses tersebut, menggantinya dengan momen komedik kala Naya tak mampu menahan goyangan tubuhnya kala mendengar aransemen Wawan dan kawan-kawan.
Hilang sudah proses memahami akar rumput sebagaimana Petris dan dan Yulia lalui. Dangdut tak lagi coba dimengerti, tapi hanya diposisikan sebagai properti tanpa arti. Deretan nomor legendaris seperti Jablay dan Mars Pembantu kembali dibawakan, masih terdengar catchy, namun dengan aransemen anyar yang kurang bernyawa (baca: kurang nakal), sama seperti filmnya sendiri. Adegan panggungnya pun dibawakan sekenanya, yang nampak dari minimnya usaha sinkronisasi antara departemen visual dengan audio.
Skripnya wajib berterima kasih pada jajaran pemain yang melaksanakan tugas masing-masing secara maksimal. Biarpun belum benar-benar mulus melakoni momen dramatik, Anya Geraldine nampak semakin bertumbuh sebagai figur lead yang solid. Sedangkan nama-nama seperti Keanu, Fajar Nugra, hingga Adi Sudirja mampu menyulap materi humor yang sejatinya medioker, jadi memiliki daya untuk memancing tawa.
Khususnya Keanu yang senantiasa total sekaligus natural dalam hal menumpahkan beragam celotehan dan ejekan menggelitik dari mulutnya. Comic timing-nya luar biasa. Bahkan di satu titik, ia memamerkan kebolehan improvisasi yang begitu kreatif nan lucu, sampai membuat lawan mainnya kesulitan menahan tawa.
Saya pun ingin menyoroti penampilan terakhir mendiang Joshua Pandelaki yang akan membuat hati banyak penonton teriris lewat aktingnya. Sayang, naskahnya gagal melahirkan drama mumpuni terkait konflik ayah-anak miliknya. Terutama saat Monty memilih memposisikan penyakit kronis selaku trik malas guna menyelesaikan permasalahan.
Saya sungguh membenci cara yang belakangan untungnya sudah mulai ditinggalkan oleh para penulis naskah ini. Mengapa eksistensi penyakit seketika mengeliminasi bobot masalah? Mengapa penyakit seolah menjustifikasi kesalahan yang penderitanya lakukan? Mengapa semuanya serba instan? Tidak adakah ruang untuk pembicaraan yang lebih mendalam?
REVIEW - PENJAGAL IBLIS: DOSA TURUNAN
Penjagal Iblis: Dosa Turunan mungkin bukan film yang akan banyak menghiasi daftar terbaik orang-orang di akhir tahun nanti, apalagi sebuah mahakarya. Tapi setidaknya ia menunjukkan bahwa andaikan sineas kita (bukan cuma yang terlibat di departemen artistik) mau sedikit saja memeras kreativitas, selalu ada cara mengolah formula arus utama supaya tak menghasilkan tontonan yang itu-itu saja.
Alkisah ada Daru (Marthino Lio), wartawan koran yang tengah mengusut dua kasus: pembantaian terhadap sebuah keluarga, dan pembunuhan berantai yang menjadikan para pemuka dari berbagai agama sebagai korban. Tommy Dewo selaku sutradara sekaligus penulis naskah punya modal berupa "premis seksi" di tangannya, terutama seputar kasus yang disebut belakangan. Rasa ingin tahu penonton bakal mudah disulut.
Sebagai protagonis, Daru pun tak kalah menarik. Selain karena ia punya dosa masa lalu yang berpotensi memancing diskusi soal etika jurnalistik, filmnya pun kerap memperdengarkan isi hati si karakter melalui voice over. Sayang, selain menjadi alat untuk menyuapi penonton dengan eksposisi alur, maupun media menyelipkan bumbu humor, "suara hati" tersebut tak menyimpan signifikansi lebih.
Di tengah penyelidikannya, Daru berkesempatan mewawancarai Ningrum (Satine Zaneta), yang dikurung di rumah sakit jiwa dengan status tersangka untuk kasus pertama. Melalui interaksi keduanya, beragam fakta mengenai dua kasus di atas perlahan terungkap, termasuk tentang keterlibatan Pakunjara (Niken Anjani) si pemilik ilmu hitam. Di sisi lain, Penjagal Iblis pun mulai memamerkan mitologi uniknya.
Menanggalkan kemonotonan unsur klenik Jawa (atau daerah mana pun di Indonesia), Tommy Dewo mengembangkan dunianya sendiri, yang sedikit mengingatkan pada kisah-kisah silat klasik yang dipertemukan dengan warna-warni fantasi. Kreatif, termasuk ketika naskahnya menjelaskan alasan mengapa si pembunuh memilih korban dari golongan tertentu, meski harus diakui beberapa konsepnya memerlukan eksplorasi lebih jauh untuk dapat disebut "matang".
Satu poin lagi yang patut disayangkan adalah minimnya upaya naskah untuk melibatkan penonton dalam perjalanan Daru mengumpulkan petunjuk. Walau sudah mempunyai voice over, kita urung dibawa menyelami proses berpikir Daru, sehingga elemen investigasinya acap kali terkesan instan. Paling kentara adalah saat Daru berhasil menemukan sebuah benda kepunyaan Ningrum yang hilang. Apa yang membuatnya terpikir untuk mencari "di sana"?
Tapi di luar beberapa kelemahan bercerita tersebut, lihat upaya filmnya menawarkan modifikasi dalam format presentasinya. Lihat bagaimana momen flashback berhasil dijauhkan dari kesan membosankan berkat penggunaan animasi yang menghadirkan parade visual unik sehingga mampu melipatgandakan daya tariknya meski kemunculannya cenderung singkat.
Sekali lagi, selalu ada cara menjauhkan kesan monoton selama si pembuat karya mau sedikit saja mencurahkan lebih banyak daya dan upaya. Tengok juga kehebatan kinerja tim efek spesialnya membungkus "adegan lahiran" di babak ketiga supaya menghadirkan kesan disturbing, tatkala banyak horor lokal medioker mungkin akan memilih cara gampang nan ala kadarnya untuk menghidupkan situasi serupa.
Sedangkan di jajaran pelakon, gerak-gerik serta kemampuan mengolah raga dari Satine Zaneta membuatnya nampak meyakinkan sebagai penjagal iblis tangguh. Tatkala pengarahan aksi Tommy Dewo di babak puncak seolah kekurangan energi, Satine menjaga nyala api filmnya supaya tidak meredup.


%20(1).png)



%20(1).png)

.png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)

%20(1).png)
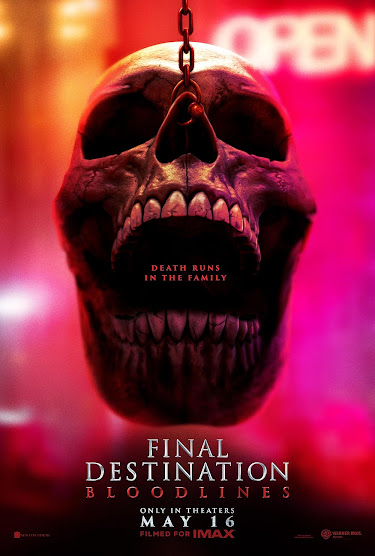
%20(1).png)

.png)

%20(1).png)



.png)
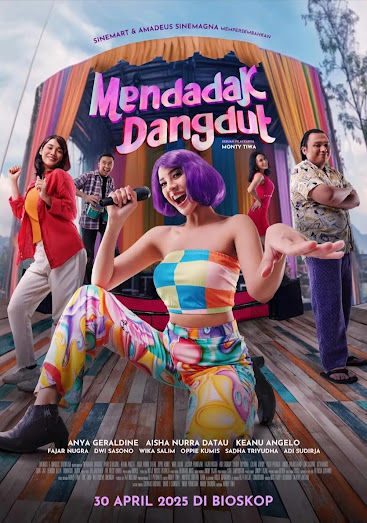


%20(1).png)








Tidak ada komentar :
Comment Page:Posting Komentar